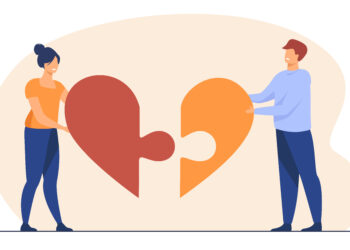SERPONG, ULTIMAGZ.com – September diperingati sebagai Bulan Kesadaran Tuli, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kepedulian terhadap penyandang tuli sekaligus menolak segala bentuk stigma yang mereka hadapi. Di tengah upaya ini, istilah ‘tone deaf’ pun kerap muncul dalam percakapan sehari-hari.
Menurut merriam-webster.com, penggunaan pertama istilah ini tercatat pada 1883 dalam konteks musik. Awalnya, tone deaf merujuk pada kondisi medis yang dikenal sebagai amusia, yaitu ketidakmampuan membedakan nada atau pitch dalam musik. Namun, seiring waktu, istilah ini berkembang menjadi metafora sastra untuk menggambarkan sikap yang tidak sensitif atau tidak peka dalam memahami isu sosial terkini, sentimen, dan opini publik.
Baca juga: Mengenal Tone Deaf, Sikap Tidak Peka Terhadap Lingkungan Sekitar
Sayangnya, menurut The Seattle Times sebagaimana dikutip oleh kumparan.com, penggunaan istilah ini termasuk sebagai contoh ableist language, bahasa yang merujuk pada ableisme. Hal ini berarti tindakan mendiskriminasi penyandang disabilitas atau memberi prasangka sehingga membatasi potensi mereka.
Kata ‘deaf’ sendiri merupakan bagian dari payung disabilitas pendengaran. Menurut akun instagram @felstarnissi, aktivis yang mewakili komunitas tuli, pelabelan tone deaf memiliki arti bahwa teman-teman tuli dianggap tidak berhubungan atau tertinggal dari dunia sekitar. Oleh karena itu, menyebut seseorang dengan label tone deaf dapat melanggengkan stigma negatif terhadap mereka.
Alternatif yang Lebih Inklusif
Alih-alih menggunakan istilah tone deaf, Ultimates bisa menggantinya dengan kata-kata yang lebih spesifik untuk menjelaskan sikap atau perilaku seseorang. Misalnya, kata seperti ‘insensitive’, ‘unaware’, ‘out of touch’, ‘ignorant’, ‘apathy’. Ultimates juga dapat gunakan kata alternatif dalam bahasa indonesia seperti ‘tidak sensitif’, ‘bebal’, ‘tidak peka’, ‘tidak peduli’, dan ‘apatis’, dilansir dari akun instagram @felstarnissi.
Penggunaan frasa alternatif di atas dapat lebih akurat menggambarkan sikap atau tindakan “kurang memperhatikan isu sosial” tanpa merujuk pada kemampuan fisik. Dengan begitu, komunikasi menjadi lebih jelas, inklusif, dan tetap menekankan perilaku, bukan keterbatasan fisik seseorang.
Istilah Ableist Bukan Hanya Tone Deaf
Istilah ableist lain seperti ‘dumb’, ‘blind eye’, ‘crazy’, hingga akhir-akhir ini ‘NPD’ (Narcissistic Personality Disorder) sering digunakan dalam keseharian tanpa disadari. Dalam artikel bbc.com disebutkan bahwa sekitar satu miliar orang di dunia merupakan penyandang disabilitas. Walaupun jumlahnya banyak, diskriminasi terhadap mereka masih terus terjadi di hampir semua lapisan masyarakat. Salah satu diskriminasi yang mereka terima yakni dalam bentuk agresi mikro linguistik, seperti penggunaan ableist language.
Rosa Lee Timm, Kepala Pemasaran Communication Service for the Deaf menyampaikan bahwa istilah tone deaf tidak hanya memarginalkan orang dengan disabilitas, tetapi juga membangun budaya pemisahan. Jamie Hale, CEO Pathfinders Neuromuscular Alliance menekankan bahwa penggunaan ableist language secara tidak langsung mengasosiasikan ketidakmampuan fisik dengan karakter buruk, dilansir dari bbc.com.
Dipengaruhi Alasan Linguistik
Menurut worthwhileconsulting.com, penggunaan ableist language banyak dipengaruhi oleh alasan linguistik. Banyak orang menggunakan kata-kata terkait gangguan penglihatan atau pendengaran untuk menjelaskan perilaku problematik. Hal ini disebabkan komunikasi manusia sering berbasis metafora konseptual.
Metafora-metafora ini terus digunakan oleh mayoritas karena sebagian besar manusia tidak mengalami disabilitas pendengaran atau penglihatan. Namun, penggunaan istilah seperti tone deaf menciptakan distorsi, seolah-olah ketidakmampuan fisik identik dengan ketidakmampuan mental atau sosial.
Turut Berdampak pada Orang Nondisabilitas
Jamie Hale menekankan bahwa efek ini tidak hanya dirasakan oleh orang dengan disabilitas, tetapi juga bisa berdampak pada nondisabilitas sendiri di kemudian hari. Misalnya, ketika mereka menua atau mengalami masalah kesehatan tertentu.
“Ketika orang nondisabilitas menggunakan bahasa yang memarginalkan (ableist language), mereka juga ikut membangun lingkungan yang menekan dan memisahkan,” ujar Hale.
Sementara itu, Rosa Lee Timm menyoroti dampak psikologis dari penggunaan istilah-istilah ableist. Ia menambahkan bahwa mengganti istilah-istilah ableist dengan deskripsi perilaku yang lebih spesifik, membuat komunikasi lebih jelas dan inklusif.
“Internalisasi bahasa yang menilai kemampuan fisik secara negatif dapat memengaruhi harga diri dan persepsi diri seseorang,” kata Timm.
Maka dari itu, penting untuk melakukan debugging bahasa, yakni memperhatikan dan mengganti istilah yang menyinggung keterbatasan fisik dengan frasa yang lebih tepat dan sesuai kenyataan.
Baca juga: Film Nonnas Hadirkan Kehangatan Restoran Melalui Dapur Nenek
Debugging bahasa bukan sekadar soal etis atau tidak etis, melainkan untuk memperkuat empati dan menghormati semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Upaya sederhana ini dapat merubah perlahan struktur diskriminatif yang sudah lama tertanam dalam masyarakat.
Mari lebih kritis terhadap dampak dari pilihan bahasa yang digunakan sehari-hari. Ayo mulai gunakan istilah alternatif atau kata-kata yang lebih spesifik untuk menggambarkan suatu sikap atau tindakan. Dengan begitu, Ultimates bisa menciptakan lingkungan yang inklusif untuk semua kelompok!
Penulis: Nasywa Agnesty
Editor: Jessie Valencia
Foto: freepik.com
Sumber: merriamwebster.com, kumparan.com, akun instagram @felstarnissi, bbc.com, worthwhileconsulting.com.